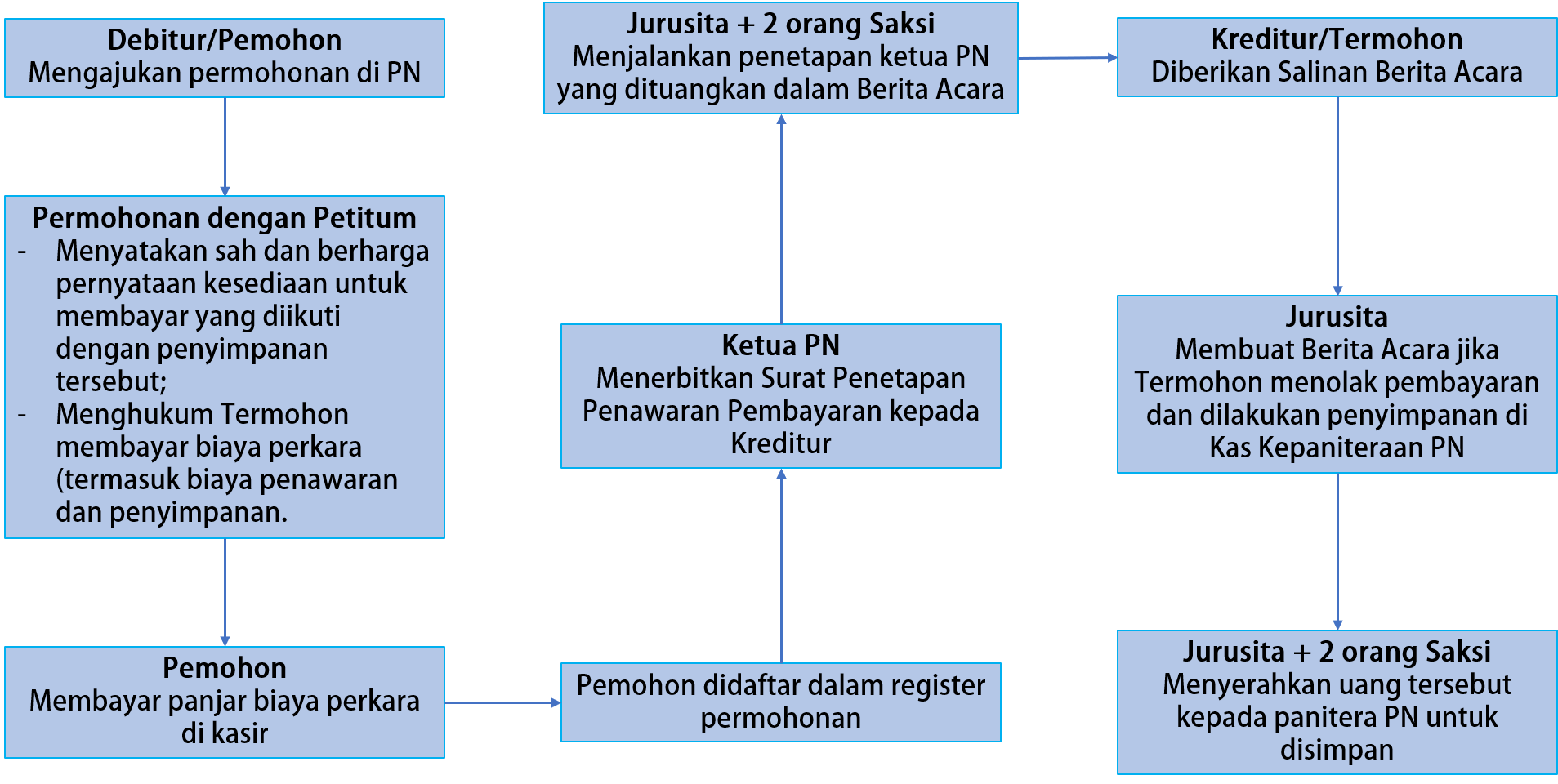Dasar Hukum & Definisi
PS diatur dalam HIR, RBG dan Rv di mana ketiganya mengatur hal-hal yang tidak jauh berbeda. Pasal 153 HIR (180 Rbg / 211 Rv), mengatur bahwa “Jika ditimbang perlu atau ada faedahnya, maka Ketua boleh mengangkat satu atau dua orang Komisaris dari pada dewan itu, yang dengan bantuan panitera Pengadilan Negeri akan melihat keadaan tempat atau menjalankan pemeriksaan di tempat itu, yang dapat menjadi keterangan bagi hakim”.
Jika melihat ketentuan tersebut maka sederhanya PS adalah pemeriksaan yang dilakukan ditempat objek perkara. Menurut Prof.Subekti, PS tidaklah lain daripada pemindahan tempat sidang hakim ke tempat yang dituju itu, sehingga apa yang dilihat oleh hakim sendiri di tempat tersebut dapat dianggap sebagai dilihat oleh hakim di muka persidangan.
Pendapat yang sama juga di-aminkan oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran No. 5 Tahun 1999 tentang Biaya Administrasi (SEMA 5/1999), menyebutkan PS sifatnya sama dengan persidangan yang dilakukan di kantor pengadilan. Tidak salah jika PS disebut sebagai metode pemeriksaan dengan cara memindahkan sidang dari gedung pengadilan ke tempat obyek perkara, dengan alasan logis tidak mungkin obyek tersebut dibawa ke dalam gedung pengadilan. Kemudian mengacu kepada pendapat Riduan Syahrani bahwa PS adalah pemeriksaan mengenai fakta-fakta atau keadaan di tempat objek perkara berada. Dari pengertian tersebut yang dapat kita ketahui lagi bahwa PS dilaksanakan untuk mencari fakta atau dilaksanakan pada sidang pembuktian (pemeriksaan alat bukti). Sehingga hemat Penulis, PS adalah metode pemeriksaan alat bukti yang dilakukan lansung di tempat obyek perkara berada.
Tata Cara
PS diatur dalam Pasal 153 HIR, Pasal 180 Rbg, Pasal 211 - 214 Rv, ketentuan-ketentuan tersebut tidak menjelaskan secara rinci bagaimana pelaksanaan PS di lapangan. Hal ini menyebabkan pelaksanaan PS menjadi mengikuti kebiasaan para hakim di pengadilan, yang bisa berbeda-beda satu sama lain. Mengambil contoh di salah satu pengadilan PS dilaksanakan dengan cara datang ke lokasi kemudian menanyakan kepada para pihak (Penggugat dan Tergugat) tekait obyek perkara. Sedangkan di tempat lain juga dilakukan dengan cara melihat alat bukti surat kemudian mencocokan dengan kondisi lapangan
Pada akhirnya tata cara ini akan berdampak pada validasi fakta yang ditemukan pada PS, coba saja kita bayangkan jika PS hanya dilaksanakan dengan meminta keterangan dari para pihak (bukan alat bukti), sudah pasti mereka akan menyebutkan sesuai dengan yang mereka tulis dalam gugatan atau jawaban. Tingkat validasi atau kebenaran fakta tersebut menjadi sangat rentan manipulasi.
Sehingga perlu dijelaskan tata cara PS berdasarkan Pasal 153 HIR, Pasal 180 Rbg, Pasal 211 - 214 Rv, SEMA 7/2001, SEMA 5/1999 kemudian disesuaikan dengan kaidah pemeriksaan alat bukti dalam acara perdata sebagai berikut:
|
No.
|
Tahap
|
Keterangan
|
|
1.
|
Dilakukan atas permintaan salah satu pihak atau oleh hakim karena jabatannya
|
Pasal 153 HIR, 180 Rbg, 211 Rv
|
|
2.
|
hakim menetapkan ongkos jalan yang ditanggung oleh pihak yang memohon PS. Jika dimintakan oleh hakim, maka ongkos PS dibebankan pada pihak yang paling berkepentingan (Penggugat). Ongkos dibayar terlebih dahulu sebelum PS dilaksanakan
|
Pasal 214 Rv, Angka 2 SEMA 7/2001, SEMA 5/1999;
SEMA 5/1999, tidak dibenarkan adanya pembebanan biaya yang bersifat honor/uang makan bagi Majelis/Hakim/Panitera Pengganti, kecuali untuk transportasi dari Kantor Pengadilan ke tempat persidangan pulang pergi;
Instruksi Dirjen Badimul No. 3207/DJU/SK/PS.01/10.2019, biaya pemeriksaan setempat terdiri dari biaya pemberitahuan 2x, transportasi dan PNBP.
|
|
3.
|
perintah melaksanakan PS dituangkan dalam putusan sela atau berita acara. Berisi penunjukan hal-hal perlu dipersiapkan termasuk alat bukti dan ongkos.
|
Pasal 153 HIR, 180 Rbg, 211 Rv
|
|
4.
|
Setelah ongkos dibayarkan kemudian dilakukan pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan antara lain kantor pemerintahan setempat (lurah/desa), kantor badan pertanahan dan pihak keamanan;
|
SEMA 7/2001, SK Dirjen Badilum 40/DJU/SK/HM.02.3./1/2019
|
|
5.
|
Pada hari yang ditentukan, hakim bersama para pihak serta pihak lain yang dipanggil melaksanakan sidang di lokasi benda yang akan diperiksa;
|
Pasal 153 HIR, 180 Rbg, 211 Rv
|
|
6.
|
Hakim dapat membuka sidang secara resmi baik di ruang sidang terlebih dahulu atau langsung pada lokasi PS;
|
Pasal 253 HIR (setiap sidang harus dinyatakan dibuka terlebih dahulu oleh Hakim)
|
|
7.
|
Para pihak diberi hak untuk mengajukan alat bukti yang memperkuat dalilnya selama PS;
|
Pemeriksaan alat bukti yang diajukan selama PS, disesuaikan dengan hukum acara pemeriksaan alat bukti pada persidangan di ruang sidang pengadilan. Untuk surat dicocokan aslinya sedangkan untuk saksi atau ahli dilakukan penyumpahan, kemudian dilakukan tanya jawab;
Angka 3 SEMA 7/2001 menyebutkan selama PS wajib memperhatikan Pasal 150 HIR;
Pasal 150 HIR mengatur mengenai tanya jawab saksi harus melalui hakim ketua.
|
|
8.
|
Dapat dilakukan pengukuran objek yang dilakukan oleh BPN, dengan biaya yang disepakati oleh kedua belah pihak
|
Angka 2 SEMA 7/2001
|
|
9.
|
Panitera Pengganti menuangkan hasil PS dalam berita acara
|
Pasal 153 HIR, 180 Rbg, 212 Rv
|
Dari yang Penulis amati di lapangan, banyak sekali pelaksanaan PS yang tidak menghadirkan alat bukti, terutama saksi dan ahli. Mungkin dikarenakan sulitnya memanggil saksi atau mungkin untuk mempercepat proses PS itu sendiri. Sebagai pengganti terkadang hanya para pihak yang dimintai keterangannya, bahkan tidak jarang kuasa hukum para pihak. Padahal Mahkamah Agung telah menegaskan dalam SEMA 5/1999 bahwa PS sifatnya sama seperti sidang di kantor pengadilan, yang artinya tidak mengesampingkan asas atau kaidah pembuktian yang mana kita ketahui keterangan para pihak atau kuasa hukumnya tidak termasuk alat bukti yang sah.
Sebagai perbandingan, tata cara PS yang melibatkan saksi sebenarnya sudah diadopsi oleh salah satu peraturan di kementerian/lembaga, dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Di Lingkungan Kementrian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Permenhan 34/2016), yang menyebutkan bahwa “Pihak Kemhan sebelum pelaksanaan PS wajib menyiapkan saksi yang dapat memberikan keterangan tentang Lokasi, Luas dan Batas dan/atau bangunan terkiat Obyek Perkara pada saat PS”. Walaupun Permenhan 34/2016 hanya berlaku di lingkungan Kemenhan, namun menurut Penulis kaidah yang diatur dalam peraturan tersebut telah telah tepat menerapkan kaidah hukum acara perdata, khususnya dalam tata cara pelaksanaan PS.
Kekuatan Pembuktian
Kemudian yang tidak kalah penting mengenai hasil PS apakah dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim? jawabannya tentu saja dapat. Dalam beberapa yurisprudensi yakni Putusan MA No. 1497 K/sip/1983, MA 3197 K/ Sip/1983, Putusan MA 1777 K/Sip/1983 hasil PS dapat menjadi patokan hakim dalam menentukan luas, letak dan batas objek perkara. Namun pertanyaannya, hasil PS seperti apa yang dapat digunakan untuk itu? Apakah hasil PS yang dilaksanakan dengan cara menanyai para pihak atau kuasanya dapat menjadi patokan?
Hal ini menurut Penulis harus dikembalikan kepada asas pembuktian dalam hukum acara perdata, yakni asas pembuktian postif yang mencari kebenaran formiil. Pada intinya kebenaran formiil mencari kebenaran yang diperoleh dari alat bukti yang sah (berbeda dengan kebenaran materiil dalam acara pidana diperoleh dari alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim). Lantas apa saja alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata ? Mari kita lihat tabel berikut (berdasarkan buku Yahya Harahap Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Bandung:2010, halaman 545 s.d 554):

Hal disebutkan dalam tabel di atas adalah alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 164 HIR, 284 Rbg, 1866 BW. Terhadap mereka sudah diatur juga masing-masing kekuatan pembuktiannya. Hemat penulis sebuah alat bukti yang sah akan memiliki kekuatan pembuktian, dimana karena kekuatan pembuktian tersebut hakim terikat untuk mempertimbangkan atau tidak sebuah alat bukti. Selama PS dilaksanakan dengan cara melibatkan alat bukti yang sah, maka fakta atau keterangan yang diperoleh akan memiliki kekuatan pembuktian. Oleh karena itu fakta atau keterangan PS tersebut menjadi alat bukti yang sah dan valid untuk digunakan dalam pertimbangan putusan.
Ada pemahaman yang berkembang mengenai PS sebagai salah satu alat bukti. Hal ini berbeda dengan yang dimaksud oleh penulis di atas, dimana yang penulis maksud adalah keterangan atau fakta yang diperoleh dari PS lah yang menjadi alat bukti, bukan kegiatan PS itu sendiri. Pandangan tersebut sebenarnya sudah dibantah baik berdasarkan SEMA 5/1999 maupun oleh ahli yakni Yahya Harahap yang menyatakan PS bukan alat bukti dan tidak memiliki kekuatan pembuktian, PS adalah metode pemeriksaan.